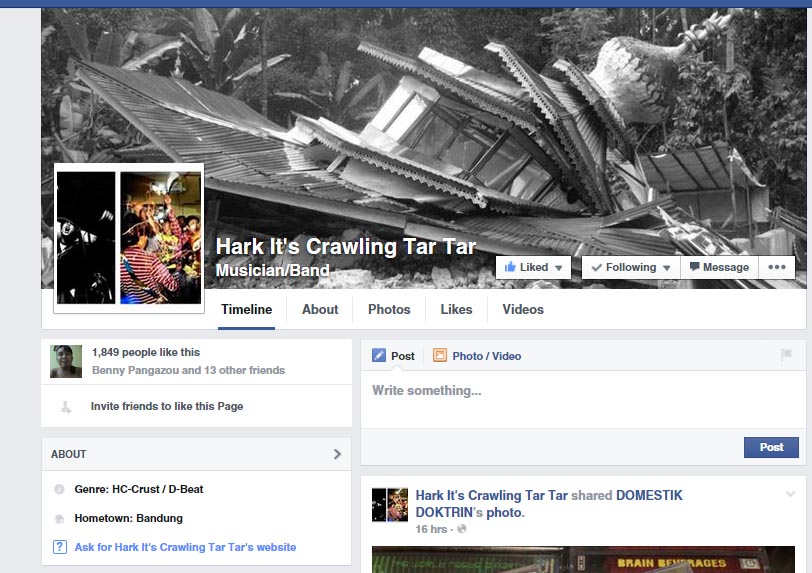SUBCHAOSZINE–Sejak Perang Dingin berakhir, banyak kalangan di Barat yang berperilaku seperti yang disarankan Samuel Huntington: agar mewaspadai Islam! Sebab, kata Huntington, dalam buku terkenalnya, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah menaklukkan Barat. (Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt, and it has done at least twice). (Huntington, The Clash of Civilization … 1996: 209-210.
Islam dan umat Islam kemudian menjadi objek studi yang sangat menjanjikan. Berbagai LSM yang mengamat-amati Islam bermunculan di Indonesia. Isu-isu yang ‘laku dijual’ adalah seputar masalah Pluralisme, kebebasan beragama, multikulturalisme, kesetaraan gender, HAM, dan sebagainya. Istilah-istilah ini sebelumnya tidak dikenal oleh umat Islam. Tapi, banyak pihak yang kemudian menjadikan paham-paham itu sebagai tolok ukur kebenaran dan standar penilaian kebaikan. Baik tidaknya seorang Muslim diukur dengan istilah “radikal”, “eksklusif”, “inklusif”, “pluralis”, “HAM” dan sebagainya.
Istilah-istilah baru itu kemudian menggusur istilah-istilah baku dalam Islam, seperti “iman”, “Islam”, “sholeh”, “taqwa”, “ihsan”, “murtad”, “musyrik”, dan sebagainya. Artinya, seorang muslim akan dikenai stigma negatif jika sudah kena label “radikal”, “eksklusif”, “anti-pluralisme”, “anti-multikulturalisme” dan sebagainya. Baik-buruknya seseorang tidak lagi diukur dengan kategori: iman-kufur, tauhid-syirik, adil-fasiq, halal-haram, dan sebagainya.
Belum lama, terbit sebuah buku berjudul Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia (2011). Buku ini diberi kata ‘Pengantar Ahli’ oleh Prof. Dr. Muhaimin, M.A., guru besar UIN Malang. Sang guru besar menulis, bahwa saat ini sudah “mendesak sekali “membumikan” pendidikan Islam berwawasan pluralisme dan multikulturalisme. Kesadaran akan pentingnya pluralisme dan multikulturalisme dipandang menjadi perekat baru integrasi bangsa yang sekian lama tercabik-cabik.” (hal. xiv).
Padahal, jika dibaca dengan serius, isi buku ini jelas-jelas mendukung liberalisasi pendidikan Islam. Disebutkan, bahwa diskursus pluralisme agama di Indonesia telah berkembang pesat. “Salah satu pertandanya adalah terbit buku Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (2004). Buku yang ditulis 8 tokoh pembela pluralisme Islam di Indonesia ini adalah Nurcholish Madjid, Kautsar Azhari Noer, Komaruddin Hidayat, Masdar F. Mas’udi, Zainun Kamal, Budhy Munawar-Rahman, Ahmad Gaus AF, Zuhairi Misrawi, dan Mun’im A. Sirry – telah memberikan terobosan fundamental terkait dengan masalah pluralisme dari sudut pemikiran keagamaan, karena mereka telah berhasil memberikan argumen teologis bagaimana pandangan Islam terhadap agama-agama lain, termasuk dalam persoalan ibadah praktis (fikh), mulai soal doa sampai pernikahan antaragama – dan sejak ini pula, argument Islam untuk pernikahan antaragama menjadi mapan, dan telah menghasilkan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.” (hal. 124).
Seperti pernah kita ungkap dalam beberapa Catatan, buku Fiqih Lintas Agama terbitan Paramadina itu memang mempromosikan pernikahan beda agama dan memmbongkar hukum Islam tentang keharaman pernikahan muslimah dengan laki-laki non-Muslim. “Soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.” (Mun’im A. Sirry (ed), Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), hal. 164).
Untuk membongkar hukum Islam, secara sistematis, buku ini mengawali uraiannya dengan melecehkan Imam Syafiirahimahullah: “Kaum Muslim lebih suka terbuai dengan kerangkeng dan belenggu pemikiran fiqih yang dibuat imam Syafi’i. Kita lupa, imam Syafi’i memang arsitek ushul fiqih yang paling brilian, tapi juga karena Syafi’ilah pemikiran-pemikiran fiqih tidak berkembang selama kurang lebih dua belas abad. Sejak Syafi’i meletakkan kerangka ushul fiqihnya, para pemikir fiqih Muslim tidak mampu keluar dari jeratan metodologinya. Hingga kini, rumusan Syafi’i itu diposisikan begitu agung, sehingga bukan saja tak tersentuh kritik, tapi juga lebih tinggi ketimbang nash-nash Syar’i (al-Quran dan hadits). Buktinya, setiap bentuk penafsiran teks-teks selalu tunduk di bawah kerangka Syafi’i.” (Ibid., hal. 5).
Jika Imam Syafii yang agung dan sangat diakui keilmuannya oleh para ulama Islam sedunia dilecehkan dan direndahkan martabatnya semacam itu, tentu kita patut bertanya, sehebat apakah manusia-manusia yang melecehkannya ini? Adakah karya-karya ilmiah hebat yang telah mereka hasilkan dan diakui oleh para ulama dan cendekiawan Muslim sedunia?
Entah mengapa saat ini sejumlah pihak mengkaitkan pluralisme, multikulturalisme, dan toleransi beragama, dengan kasus pernikahan beda agama. Orang yang menolak pernikahan beda agama dicap sebagai tidak toleran, tidak pluralis, tidak berwawasan multikultural, dan sebagainya. Saat ini bermunculan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang membuat laporan tentang kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia.
Sesuai dengan panduan al-Quran (49:6), maka orang Muslim diajar untuk bersika kritis, tidak bersikap apriori, asal tolak atau asal terima saja. Telitilah informasi itu. Darimana sumbernya, dan bagaimana kebenaran logika dan argumentasi yang digunakannya. Jika memang yang membawa berita adalah kaum fasik, maka berhati-hatilah!
Satu contoh lain dari analisis yang keliru dilakukan oleh Setara Institute dalam memandang konsep kerukunan beragama dan kaitannya dengan peran kelompok fundamentalis. Kelompok yang mengusung jargon “Institute for Democracy and Peace” ini – dalam buku terbitannya yang berjudul Wajah Para ‘Pembela’ Islam, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010), menyimpulkan bahwa kelompok Islam fundamentalis atau Islam radikal sering mengganggu kebebasan beragama/berkeyakinan warga masyarakat lain.
“Dengan mengenali organisasi-organisasi Islam radikal, diharapkan sejumlah langkah dapat dilakukan oleh negara untuk menghapus intoleransi dan diskriminasi agama/keyakinan. Menegakkan hukum bagi para pelaku kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi serta melakukan deradikalisasi pandangan, perilaku dan orientasi keagamaan melalui kanal politik dan ekonomi adalah rekomendasi utama penelitian ini.” (hal. iv).
Salah satu kriteria untuk mengukur kadar toleransi suatu masyarakat adalah kesediaan untuk menerima perpindahan agama dan penerimaan terhadap pernikahan beda agama. Hasil survei kelompok ini di Jabodetabek, menunjukkan angka, 84,13 persen masyarakat tidak suka akan pernikahan beda agama. Lalu disimpulkan: “Dari temuan survei ini terlihat bahwa untuk perbedaan identitas dalam lingkup relasi sosial yang lebih luas (berorganisasi, bertetangga, dan berteman) masyarakat Jabodetabek secara umum lebih memperlihatkan sikap toleran. Namun, dalam lingkup relasi yang lebih personal dan menyangkut keyakinan (anggota keluarga menikah dengan pemeluk agama lain atau pindah ke agama lain) sikap mereka cenderung kurang toleran.” (hal. 65).
Survei itu juga menunjukkan data, bahwa orang yang beragama Islam menunjukkan penolakan yang lebih tinggi (82,6 persen) terhadap anggota keluarganya yang berpindah agama. Sementara, pemeluk agama selain Islam ada 45,4 persen yang menyatakan dapat menerima anggota keluarganya berpindah agama, karena soal agama adalah urusan pribadi. (hal. 66). Terhadap orang yang tidak beragama, hanya 25,2 persen responden yang menyatakan dapat menerima, karena menganggap agama hanyalah urusan pribadi. Terhadap fenomena ini, disimpulkan: “Singkatnya, secara umum tidak ada toleransi atas orang-orang yang tidak beragama. Tidak beragama masih dianggap sebagai sebuah tabu yang tidak dapat ditoleransi di mata kaum urban Jabodetabek.” (hal. 67).
Sikap responden terhadap aliran Ahmadiyah, hanya 28,7 persen yang berpendapat Ahmadiyah memiliki hak untuk menganut keyakinan mereka. Sedangkan 40,3 persen menganggap Ahmadiyah sesat, dan 45,4 persen menyatakan, sebaiknya AShmadiyah dibubarkan oleh pemerintah. Lalu dibuatlah komentar: “Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan sikap keagamaan yang intoleran pada masyarakat Jabodetabek. Agar tidak mengakibatkan kerancuan pemahaman, maka perlu digarisbawahi bahwa kecenderungan toleran untuk beberapa hal, namun intoleran untuk sejumlah hal lain sebagaimana ditunjukkan oleh temuan survei ini, tetap harus dinyatakan sebagai ekspresi sikap intoleran. Hal ini didasarkan atas pengertian toleransi sebagai kemampuan dan kerelaan untuk menerima segala bentuk perbedaan identitas pihak lain secara penuh. Atas dasar itu, kegagalan untuk dapat menerima perbedaan identitas secara utuh sama maknanya dengan sikap intoleran.” (hal. 75).
De-Islamisasi bahasa
Pakar sejarah dan linguistic, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas sudah lama mengingatkan bahaya dari sebuah proses yang disebut “de-Islamization of language”. Bahasa adalah alat untuk memahami Islam. Dulu, saat Islam masuk dan menyebar di wilayah Nusantara, bahasa Melayu menjadi alat yang efektif, setelah melalui proses Islamisasi. Bahasa yang semula hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara, kemudian diperkaya dengan “istilah-istilah kunci” dalam Islam, seperti Allah, adil, taqwa, hikmah, ilmu, akal, fikir, dan sebagainya. Dengan istilah-istilah itu, maka seseorang menjadi mudah memahami konsep-konsep pokok dalam Islam.
Proses de-Islamisasi bahasa Melayu-Indonesia kini terus berlangsung sejalan dengan proses westernisasi. Istilah-istilah “toleran”, “kerukunan”, “radikal”, dimasukkan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia dengan makna yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Orang tua yang tidak mau merestui pernikahan anaknya dengan orang yang berbeda agama dicap tidak toleran. Begitu juga orang tua yang tidak menerima anak atau anggota keluarga yang berpindah agama.
Tentu saja, dalam pandangan Islam, apa yang dilakukan oleh lembaga survei semacam itu jelas sangat keliru. Lembaga ini telah mengaburkan dan merusak makna toleransi. Orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran agamanya diberi cap intoleran dan radikal. Ini juga suatu kezaliman. Lebih disayangkan juga, bahwa di antara tokoh penting yang menyebarkan konsep “kesetaraan” dan toleran yang keliru itu adalah Muslim.
Kaum Muslim secara umum tentu akan menolak konsep toleransi semacam itu. Dalam artikelnya di Jurnal Islamia Republika (Kamis, 15/12/2011) ulama muda NU Muhammad Idrus Ramli, menulis beberapa rambu-rambu dalam bertoleransi. Menurut Gus Idrus, para ulama fuqaha dari berbagai madzhab membolehkan seorang Muslim memberikan sedekah sunnah kepada non Muslim yang bukan kafir harbi. Demikian pula sebaliknya, seorang Muslim diperbolehkan menerima bantuan dan hadiah yang diberikan oleh non Muslim. Para ulama fuqaha juga mewajibkan seorang Muslim memberi nafkah kepada istri, orang tua dan anak-anak yang non Muslim.
Di sisi lain, karena seorang Muslim bertanggungjawab menerapkan basyiran wa nadziran lil-‘alamin, Islam melarang umatnya berinteraksi dengan non Muslim dalam hal-hal yang dapat menghapus misi dakwah Islam terhadap mereka. Mayoritas ulama fuqaha tidak memperbolehkan seorang Muslim menjadi pekerja tempat ibadah agama lain, seperti menjadi tukang kayu, pekerja bangunan dan lain sebagainya, karena hal itu termasuk menolong orang lain dalam hal kemaksiatan, ciri khas dan syiar agama mereka yang salah dalam pandangan Islam. “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Ma’idah : 2).
Tentang Doa bersama Lintas Agama, Idrus menulis, bahwa dewasa ini juga agak marak dilakukan. Sebagian beralasan Islam rahmatan lil-‘alamin. Padahal, karakter rahmatan lil-‘alamin, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan doa bersama lintas agama. Sebagaimana dimaklumi, doa merupakan inti dari pada ibadah (mukhkhul ‘ibadah), yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan. Tidak jarang, seorang Muslim berdoa kepada Allah, dengan harapan memperoleh pertolongan agar segera keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Tentu saja, ketika seseorang berharap agar Allah segera mengabulkan doanya, ia harus lebih berhati-hati, memperbanyak ibadah, bersedekah, bertaubat dan melakukan kebajikan-kebajikan lainnya. Dalam hal ini, semakin baik jika ia memohon doa kepada orang-orang shaleh yang dekat kepada Allah. Hal ini sebagaimana telah dikupas secara mendalam oleh para ulama fuqaha dalam bab shalat istisqa’ (mohon diturunkannya hujan) dalam kitab-kitab fiqih.
Ada dua pendapat di kalangan ulama fuqaha, tentang hukum menghadirkan kaum non Muslim untuk doa bersama dalam shalat istisqa’. Pertama, menurut mayoritas ulama (madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali), tidak dianjurkan danmakruh menghadirkan non-Muslim dalam doa bersama dalam shalat istisqa’. Hanya saja, seandainya mereka menghadiri acara tersebut dengan inisiatif sendiri dan tempat mereka tidak berkumpul dengan umat Islam, maka itu tidak berhak dilarang.
Kedua, menurut madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Maliki, bahwa non Muslim tidak boleh dihadirkan atau hadir sendiri dalam acara doa bersama shalat istisqa’, karena mereka tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Doa istisqa’ ditujukan untuk memohon turunnya rahmat dari Allah, sedangkan rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Demikian kesimpulan pendapat ulama fuqaha dalam kitab-kitab fiqih. Maka, jika doa diharapkan mendatangkan rahmat dari Allah, sebaiknya didatangkan orang-orang saleh yang dekat kepada Allah, bukan mendatangkan orang-orang yang yang jauh dari kebenaran.
Forum Bahtsul Masail al-Diniyah al-Waqi’iyyah Muktamar NU di PP Lirboyo Kediri, 21-27 November 1999, menyatakan, bahwa “Doa Bersama Antar Umat Beragama” hukumnya haram. Diantara dalil yang mendasarinya: Kitab Mughnil Muhtaj, Juz I hal. 232: “Wa laa yajuuzu an-yuammina ‘alaa du’aa-ihim kamaa qaalahu ar-Rauyani li-anna du’aal kaafiri ghairul maqbuuli.” (Lebih jauh, lihat: Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004), penerbit: Lajtah Ta’lif wan-Nasyr, NU Jatim, cet.ke-3, 2007, hal. 532-534). (Wallahu a’lam).*
Kontribusi : Bang Adian